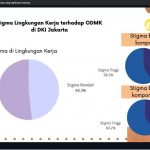Indonesia akan menjadi negeri produktif dengan pekerja sebagai faktor utama pembangunan, termasuk pekerja penyandang disabilitas. Mereka memiliki hak yang sama untuk berkontribusi pada bangsa. Hal ini terlihat dari adanya Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 yang mengatur Aspek Penyandang Disabilitas pada Pekerja.
Berdasarkan UU tersebut, beberapa hak yang didapat pekerja penyandang disabilitas, antara lain memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau swasta tanpa diskriminasi; memperoleh upah yang sama dengan tenaga kerja yang bukan penyandang disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama; memperoleh akomodasi yang layak dalam pekerjaan; tidak diberhentikan karena alasan disabilitas; mendapatkan program kembali bekerja; penempatan kerja yang adil, proporsional, dan bermartabat; serta memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karier serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya.
Menurut Direktur Bina Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Dr. Nora Kartika Setyaningrum, S.E., M.Si., komitmen dari negara jelas di seluruh undang-undang. Sesuai dengan amanah konstitusi, negara mengatur setiap orang agar tidak melakukan diskriminasi kepada penyandang disabilitas. Sebagaimana tertulis pada Pasal 53 Ayat 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, bahwa pemerintah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) harus mempekerjakan penyandang disabilitas paling sedikit 2% dan perusahaan swasta 1%. Namun, adanya stigma dan stereotype negatif membuat diskriminasi cenderung terekspos dalam bentuk kekerasan dan pelecehan, termasuk di tempat kerja.
“Meski hak para penyandang disabilitas telah diatur, kita sering menjumpai adanya pemahaman yang keliru dari masyarakat terkait pekerja disabilitas. Kekeliruan ini menimbulkan stereotype negatif sehingga memberikan stigma dan diskriminasi yang berujung pada persekusi dan pengucilan,” kata Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat UI, Prof. dr. Mondastri K. Sudaryo M.S., D.Sc., dalam webinar “Perlindungan Sosial dan Stigma bagi Pekerja dengan Disabilitas”, pada Selasa (14/06) lalu.
Terkait pemetaan pekerja disabilitas di Indonesia, penyandang disabilitas yang paling banyak mendapatkan pekerjaan berada di usia produktif, yaitu usia 15–24 tahun. Walaupun tingkat pendidikannya lebih rendah, penyandang disabilitas di desa lebih banyak yang mendapatkan pekerjaan dibandingkan dengan penyandang disabilitas di perkotaan. “Sangat sedikit penyandang disabilitas yang mendaftar pekerjaan sendiri, misalnya melalui job fair. Kebanyakan mereka mendapatkan pekerjaan dari keluarga atau kenalan yang telah bekerja,” kata Perwakilan International Labour Organization, Tendy Gunawan, S.T., M.Sc.

Tantangan bagi disabilitas dalam bekerja adalah masih banyaknya perusahaan, baik milik negara maupun swasta, yang menganggap disabilitas sebagai hambatan. Dampaknya, penyandang disabilitas cenderung tidak bisa menyampaikan disabilitasnya dengan jujur karena merasa khawatir tidak akan diterima karena adanya stigma tersebut. Tantangan lain bagi penyandang disabilitas adalah hambatan berupa infrastruktur kantor yang kurang memadai, kemampuan beradaptasi dengan teknologi, serta akomodasi menuju tempat kerja yang tidak tersedia.
“Perlu dilakukan perumusan strategi dan evaluasi dalam pengelolaan kelompok disabilitas dalam bekerja agar dibuat dengan adil. Selain itu, harus dibangun sistem non-diskriminasi di tempat kerja sebagai solusi untuk mengatasi tantangan yang dihadapi pekerja disabilitas,” kata drg. Romi Syofpa Ismael, penyandang disabilitas yang pernah diperbincangkan karena perjuangannya menjadi CPNS pada 2019 silam.
Selain penyandang disabilitas, stigma negatif juga diterima Orang dengan HIV AIDS (ODHA). Mitra Peneliti dari Pusat Penelitian HIV AIDS (PPH) PPH, Dr. Octavery Kamil, M.Si., bersama tim memaparkan kasus ODHA pada komunitas di Kabupaten Tangerang yang kerap menerima stigma hingga menyebabkan depresi karena penyakit HIV yang dideritanya.
Hasil penelitian menunjukkan, perceived stigma paling tinggi dialami ODHA laki-laki berusia 26–35 tahun, sedangkan perceived stigma paling rendah dialami ODHA dengan pendidikan perguruan tinggi dan bekerja yang terdiagnosis 1 tahun. Untuk mengatasi hal ini, perlu ditingkatkan upaya dan pengembangan program pemerintah terkait pendampingan ODHA melalui puskesmas dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang ada di Kabupaten Tangerang.
Sementara itu, stigma negatif juga diberikan kepada Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) di DKI Jakarta. Menurut Dosen Kesejahteraan Sosial FISIP UI, Dini Widiarsih, Ph.D., dan tim, hal ini harus diatasi dengan memperbesar akses informasi dan pendidikan tentang ODMK sehingga dapat mereduksi stigma dan tindakan diskriminasi pada ODMK. Kesehatan jiwa juga perlu dipromosikan sebagai topik kajian kebijakan yang bersifat interdisipliner, interseksional, dan lintas sektor. Selain itu, perlu diadakan program edukasi dan sharing session bersama dengan ODMK atau melibatkan ODMK untuk menambah pengalaman dan mengurangi rasa takut terhadap ODMK sehingga stigma di lingkungan kerja dapat menurun.
Penulis: Nabila Sahma Libriyanti| Editor: Sapuroh