Fenomena alam yang terjadi di Palu dan Donggala kini sedang menjadi tajuk hangat berbagai media, terlebih lagi munculnya fenomena likuifaksi membuat banyak akademisi pun memberikan pandangannya tentang Palu dan fenomenanya.
Menanggapi fenomena tersebut, Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia bekerja sama dengan Fakultas Teknik menyelenggarakan diskusi ilmiah dengan tajuk “Bencana Palu: Refleksi Lingkungan, Teknis, Sosial dan Tata Ruang”, pada Senin (09/10) di Universitas Indonesia (UI) Salemba.
Prof. Dr. Budi Susilo Supanji yang merupakan pakar di bidang Geoteknik dan Manajemen Konstruksi berpendapat bahwa fenomena likuifaksi pada wilayah Palu dan Donggala terjadi karena kondisi lapisan dasar tanah yang berupa material pasir atau lanau.
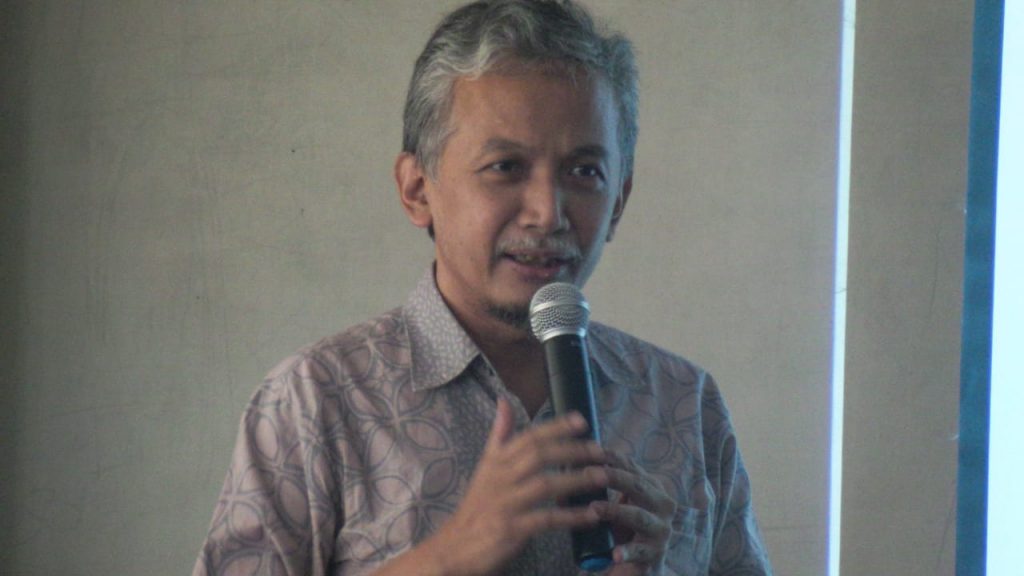
“Sebenarnya kondisi tersebut dapat dikatakan aman jika berada pada lokasi yang bukan merupakan ring of fire seperti pulau Kalimantan”, ucap Budi. Begitu pula dengan Prof. Dr. Widjojo Adi Prakoso selaku Kepala Lab. Geoteknik UI berpendapat bahwa sebenarnya zonasi sudah sejak lama diidentifikasikan bahwa wilayah tersebut memang merupakan pertemuan tiga lempeng tektonikya itu lempeng Indo-Australia, Pasifik dan Eurasia sehingga rawan terjadinya gempa bumi.
Gempa bumi dan tsunami turut menyebabkan likuifaksi semakin cepat terjadi. Namun, fakta tersebut rupanya tak tersosialisasi baik kepada masyarakat yang tetap mendirikan bangunan di daerah tersebut.
Hal ini menjadi persoalan yang pelik, dimana masyarakat saat ini pun dalam membangun bangunannya tidak pernah awas terhadap kondisi tanah saat sebelum mendirikan bangunannya. Lalu, seringnya penggunaan jasa tukang yang tidak didasarkan dengan ilmu tentang tanah dan bangunan.

Alasan utama karena biayanya yang ditawarkan jauh lebih murah. Memang ini merupakan isu sederhana, namun berdampak besar.“Pasalnya sudah ada aturan khusus seperti perundang-undangan mengenai tanah serta mendirikan bangunan yang berusaha mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan tersebut. Bahkan, ada peraturan pemerintah lainnya yang menjelaskan bahaya likuifaksi”, ucap Widjojo.
Beberapa peringatan pun telah diberikan, tetapi kerap kali hal ini ditanggapi dengan aksi penolakan dan perilaku masyarakat yang berujung pada kerusakan/vandalism seperti pencabutan sepihak plang pemberitahuan yang diberikan pemerintah daerah/kota.
Pencegahan sebenarnya dapat dilakukan dengan cara penggunaan mikrozonasi untuk memetakan wilayah-wilayah secara detil guna mengetahui wilayah mana saja yang cocok dibangun.
Kondisi tanah yang berpotensi likuifaksi pun bukan berarti tidak dapat digunakan. Menurut Prof. Budi, dengan menggunakan rekayasa penggantian gradasi tanah sejauh 15-20 meter, permasalahan ini dapat segera terpecahkan.
Namun, optimisme ini seketika luntur karena proses ini memerlukan biaya yang besar, dan alat yang canggih untuk melakukan rekayasa tersebut.Akhirnya, saran perbaikan sendiri untuk kota Palu masih terus diperdebatkan. Beberapa praktisi menganggap bahwa kondisi tanah dapat direkayasa, tetapi beberapa akademis melihat bahwa sebaiknya kota Palu dipindahkan untuk mengurangi resiko yang berulang.



